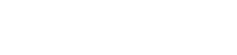Ridho Al-Hamdi*
Dinamika kepemimpinan di Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari konteks dinamika politik nasional di Indonesia. Relasi Muhammadiyah dengan pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi melahirkan tipologi kepemimpinan yang berbeda-beda.
Gaya kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo di era Orde Lama tentu memiliki perbedaan dengan gaya kepemimpinan AR Fachruddin dan Ahmad Azhar Basyir di Era Orde Baru.
Begitu juga dengan gaya kepemimpinan Muhammadiyah di era Reformasi yang melahirkan tipologi kepemimpinan yang berbeda-beda.
Langgam kepemimpinan di Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh para elitenya sehingga tipologi kepemimpinan elite di organisasi sosial-keagamaan seperti Muhammadiyah sangat merepresentasikan kondisi ummat di bawah.
Kajian tentang Kepemimpinan Elite Muhammadiyah
Sejumlah ilmuwan Muhammadiyah pernah melakukan penelitian terkait dengan kepemimpinan di Muhammadiyah.
Haedar Nashir (2000) melakukan riset di Pekajangan, Pekalongan, Jawa Tengah, yang kemudian menyimpulkan tipologi kepemimpinan elite Muhammadiyah di era Orde Baru cenderung mengarah pada perilaku moderat-akomodatif.
Syarifuddin Jurdi (2005) dalam penelitiannya di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengungkapkan sebuah temuan, bahwa perilaku politik elite Muhammadiyah dalam politik praktis mengarah pada dua model utama: sikap ideal dan sikap pragmatis.
Sikap ideal cenderung pada sikap kurang kooperatif terhadap pemerintah sementara sikap pragmatis cenderung dapat bekerjasama dengan pemerintah.
Dalam konteks pemilu 2009, David Efendi (2014) mengklasifikasikan sikap politik elite Muhammadiyah ke dalam lima varian. Pertama, kubu fundamentalisme politik: cenderung aktif dalam politik praktis karena menganggap mendapatkan legitimasi historis era Masyumi. Kedua, kubu moderat pasif: berada di tengah-tengah, tidak berpihak pada kubu tertentu. Ketiga, kubu moderat aktif: mengikuti perkembangan politik secara aktif untuk menentukan sikap politik pribadi dan jamaahnya. Keempat, kubu khittahisme: mengikuti keputusan organisasi secara taat. Kelima, kubu apolitis, terbagi dua: mereka yang berteriak Muhammadiyah apolitis dan mereka yang benar-benar apolitis dan fokus pada urusan ibadah saja.
Dalam konteks respon terhadap perkembangan isu seputar Islam dan politik, hasil penelitian Ridho Al-Hamdi (2018) mengategorisasikan pemikiran elite Muhammadiyah ke dalam empat varian: transformatik-idealistik, moderat-idealistik, realistik-kritis, dan akomodatif-pragmatis.
Keempat varian tersebut pada prinsipnya menunjukkan kenyataan, bahwa tidak ada varian pemikiran elite Muhammadiyah yang mengarah pada pemikiran fundamentalis-radikal maupun simbolistik-tekstualis. Hematnya, pemikiran moderat tetap mendominasi cara berpikir di kalangan elite Muhammadiyah.
Dalam hasil penelitian disertasi Syaifullah (2019) diungkap, bahwa strategi dan capaian Muhammadiyah dalam meraih kekuasaan baik melalui strategi struktural (era Orde Lama) maupun strategi kultural (era Reformasi) di lingkaran kekuasaan tidak jauh berbeda satu sama lain. Artinya, eksistensi Muhammadiyah tetap diperhitungkan dalam kontestasi pertarungan kekuasaan.
Potret Kepemimpinan Muhammadiyah Era Reformasi
Dari kelima kajian yang telah dikemukakan oleh Nashir (2000), Jurdi (2005), Efendi (2014), Al-Hamdi (2018), dan Syaifullah (2019), ada beberapa fakta tentang kepemimpinan Muhammadiyah di Era Reformasi.
Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial-keagamaan tidak bisa melepaskan dirinya dari situasi politik di sekitarnya. Meskipun secara tegas menjaga diri dari politik praktis, sikap dan pandangan politik Muhammadiyah menjadi salah satu penentu nasib dan masa depan republik ini.
Kedua, gerakan politik Muhammadiyah di Era Reformasi adalah gerakan politik kultural di mana Muhammadiyah tidak terlibat secara aktif dalam struktur dan institusi-institusi politik maupun pemerintahan. Ini yang dalam pandangan Amien Rais disebut sebagai “politik adiluhung” (high politics) di mana Muhammadiyah tidak terjebak dalam politik kekuasaan maupun politik kepemiluan tetapi menjadi bandul penentu dalam momen-momen strategis kebangsaan.
Meskipun corak gerakan Muhammadiyah di Era Reformasi dalam konteks kekuasaan mengambil langkah strategi kultural, peran penting tokoh di pusat pergerakan Muhammadiyah sangat menentukan model strategi kultural yang diambil oleh Muhammadiyah.
Sejak pasca-1998, Muhammadiyah telah mengalami setidaknya empat kali muktamar yang menghasilkan pucuk pimpinan yang berbeda-beda. Situasi di sekitar 1998, kepemimpinan elite Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari sosok Amien Rais yang sangat fenomenal dan menjadi representasi dari tokoh reformasi saat itu.
Barulah kemudian, sejak muktamar 2000 terjadi pergeseran kepemimpinan meskipun sejak 1998, posisi Amien Rais sudah tergantikan oleh Ahmad Syafii Ma’arif. Kepemimpinan Syafii Ma’arif (1998-2005) dilanjutkan oleh sosok intelektual muda yang berkharisma saat itu, Din Syamsuddin, untuk dua periode (2005-2015).
Setelah itu, dilanjutkan oleh sosok intelektual cum-aktivis bernama Haedar Nashir (2015-2022). Masing-masing dari tipologi kepemimpinan mereka sangat mewarnai pola gerakan Muhammadiyah.
Kepemimpinan Ahmad Syafii Ma’arif di Muhammadiyah
Di bawah Syafii Ma’arif, lahir berbagai gerakan intelektual terutama dari generasi muda Muhammadiyah seperti Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), Majelis Reboan, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), Maarif Insitute, Pusat Studi Muhammadiyah (PSM), dan lain sebagainya.
Gerakan intelektualitas terasa sangat mewarnai Muhammadiyah di bawah langgam kepemimpinan Buya Syafii Ma’arif. Selain itu, gerakan toleransi dan perdamaian juga sudah dibangun antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di bawah kepemimpinan Buya Syafii Ma’arif dan Hasyim Muzadi.
Kepemimpinan Din Syamsuddin
Sementara itu, di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin, gerakan internasionalisasi Muhammadiyah sangat terasa di mana kapasitas Din yang sudah melegenda di dunia internasional sangat berdampak pada peran Muhammadiyah di berbagai negara terutama urusan perdamaian dan dialog antar-agama (inter-faith dialogue). Munculnya Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di berbagai negara pun mulai menjamur di era Din.
Namun demikian, relasi Muhammadiyah dengan pemerintah selama kepemimpinan Din, mengarah pada relasi kurang kooperatif. Din cenderung melemparkan ktitik daripada pujian terhadap rezim SBY, yang dalam kategori Jurdi (2005) disebut sebagai “sikap ideal”.
Moderatisme Haedar Nashir
Lain Din lain pula Haedar. Jika Din mengambil jarak dengan rezim pemerintahan pada saat itu, Haedar mengambil sikap moderat dalam relasinya dengan pemerintah.
Dalam berbagai kesempatan, baik Haedar maupun Jokowi saling berbalas kunjungan. Apakah Jokowi berkunjung ke “istana Muhammadiyah” di Menteng Raya 62 atau Haedar menerima undangan ke istana presiden.
Meski situasi politik nasional menunjukkan polarisasi akibat menguatnya populisme Islam, elit Muhammadiyah berupaya menjaga hubungan moderat dengan banyak kalangan termasuk dengan pemerintah.
Apalagi, pada Pilpres 2019 ketika polarisasi semakin menguat di kalangan arus bawah Muhammadiyah. Terutama karena ditunjukkan oleh ekspresi elektoral yang beragam dalam memilih calon presiden. Dan bermunculannya komunitas relawan untuk mengekspresikan dukungan kepada masing-masing kandidat yang ada. Ini menunjukkan bahwa kader Muhammadiyah tersebar dalam berbagai ruang politik praktis.
Tipologi Kritis versus Tipologi Kooperatif
Secara eksplisit, tipologi kepemimpinan elite Muhammadiyah di era Reformasi dapat dianalisa terutama sejak peta politik Indonesia menerapkan sistem presidensial di mana SBY terpilih sebagai presiden secara langsung oleh rakyat, bukan sistem parlementer.
Selama republik ini dipimpin oleh SBY, Muhammadiyah dipimpin oleh Din Syamsuddin. Selama satu dekade ini pula, posisi Din sangat jelas terhadap pemerintah: kritis dan menjaga jarak. Artinya, langgam kepemimpinan Din mewakili tipologi kritis.
Sementara itu, sejak Jokowi memimpin republik ini, Haedar terpilih untuk menggantikan Din memimpin Muhammadiyah. Selama Haedar memimpin persyarikatan, kerjasama dan relasi baik terjalin di antara keduanya meski sebenarnya Haedar tak jarang menyampaikan pesan-pesan kritis terhadap rezim.
Berbagai faktor sangat mempengaruhi pola relasi baik tersebut dapat terwujud. Karena itu, langgam kepemimpinan Haedar sangat representatif mewakili tipologi kooperatif. Dua langgam kepemimpinan, yaitu Din dan Haedar, dapat menjadi tipologi mainstream kepemimpinan Muhammadiyah di Era Reformasi.
Sementara itu, kubu Din diperkuat lagi dengan peran Amien Rais terutama sejak Pilpres 2014 meskipun mereka sempat tidak berada dalam satu pandangan di banyak hal. Sementara kubu Haedar diperkuat dengan gaya tegas Buya Syafii Ma’arif yang dekat dengan Taufik Kiemas Cs.
Dengan demikian, tipologi kritis dapat ditemuan pada langgam kepemimpinan Din Syamsuddin dan Amien Rais. Sementara tipologi kooperatif dapat termanifestasikan pada langgam kepemimpinan Haedar Nashir dan Syafii Ma’arif meski mereka tetap bersikap kritis juga terhadap rezim.
Lalu ke mana sejatinya tipologi kepemimpinan Muhammadiyah yang ideal di Era Reformasi: apakah mengarah pada tipologi kritis atau tipologi kooperatif? Sejarah telah memberikan fakta bahwa Muhammadiyah pernah memiliki kedua tipologi tersebut.
Tentu, faktor lain sangat menentukan terhadap lahirnya tipologi kepemimpinan elite Muhammadiyah. Nah, muktamar Muhammadiyah di penghujung 2022 menjadi jawaban, apakah Muhammadiyah akan kembali mengambil posisi yang cenderung kooperatif atau menghasilkan posisi yang cenderung kritis seperti yang pernah terjadi di era sebelumnya? Muktamarin lah yang menjadi penentunya.
*Penulis adalah Wakil Dekan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah
Editor: Fauzan AS