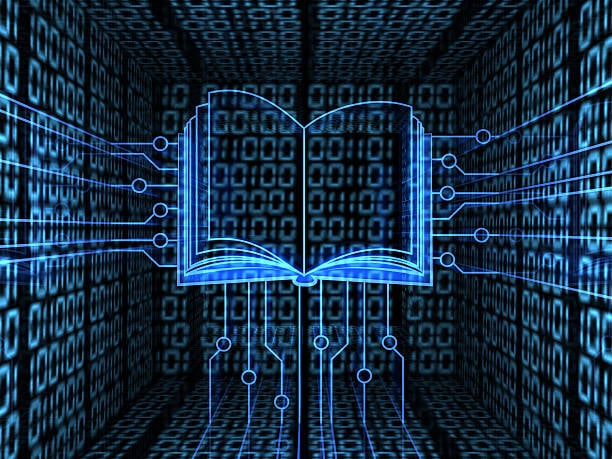MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA, – Di tengah derasnya arus teknologi dan kecerdasan buatan (AI) yang mendominasi berbagai sektor, pertanyaan mengenai relevansi filsafat kian mengemuka. Apa urgensi ilmu langka ini di era yang serba pragmatis?
Pertanyaan fundamental inilah yang menjadi sorotan utama dalam dialog podcast antara Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syifa Amin Widigdo dan Cendekiawan Muslim Syamsuddin Arif di kanal Wonderhome Library, Sabtu (26/07).
Syamsuddin Arif secara tegas menyatakan bahwa mereka yang mempertanyakan kegunaan empiris filsafat, khususnya dalam konteks pemikiran Ibnu Sina, sesungguhnya belum memahami klasifikasi ilmu. Mengutip Muhammad bin Abdul Karim Asyahrastani dalam kitab Al-Milal wa an-Nihal, Arif menjelaskan bahwa ilmu terbagi menjadi dua: ilmu teoritis dan ilmu praktis.
“Pertanyaan ‘apa gunanya, apa manfaat empirisnya’ itu untuk ilmu praktis,” ujar Arif. “Kalau untuk ilmu praktis, pertanyaan itu tidak perlu karena sudah pasti memang untuk dipraktikkan, ada kegunaan pragmatisnya.”
Namun, berbeda halnya dengan ilmu teoritis. Ilmu ini, menurut Arif, dipelajari “untuk mengetahui saja” atau knowledge for the sake of knowledge. Tujuannya adalah untuk “mengetahui yang hak, mengetahui yang benar, knowing the truth.” Sementara itu, ilmu praktis berorientasi pada knowing the good.
Keseimbangan Teori dan Praktik
Arif menekankan bahwa manusia dapat mencapai kesempurnaan sebagai makhluk rasional dan berakal apabila mempelajari keduanya: know how (ilmu praktis) dan know what serta know why (ilmu teoritis).
Bagi Syamsuddin, pendidikan tinggi sejatinya bertujuan membangun analytical mind atau kemampuan berpikir mendalam dan rasional yang tidak selalu langsung terhubung dengan dunia industri.
Ia mencontohkan pengalamannya dengan seorang dosen akuntansi bergelar PhD dari Selandia Baru, yang mengungkapkan bahwa studi S2 dan S3 akuntansi tidak lagi fokus pada perhitungan, melainkan pada konsep, teori, dan nilai.
“Nilai-nilai itu tidak ada manfaatnya sebenarnya, ada tapi indirect, tidak langsung,” jelas Arif.
Ia menganalogikannya dengan tujuan instruksional umum dan khusus dalam pendidikan matematika. Meskipun matematika digunakan untuk berhitung dalam kehidupan sehari-hari, tujuan utamanya adalah membangun analytical mind dan analytical skill.
Syifa Amin Widigdo menambahkan bahwa pada akhirnya, keilmuan apa pun akan mencapai level teoritisnya. “Matematika di mana ya praktisnya untuk ngitung jual beli sehari-hari, tapi keilmuannya itu kan juga sangat sangat teoritis,” kata Widigdo. ‘
Keduanya sepakat bahwa keseimbangan antara pengetahuan di level filosofis (know why and what) dan know how harus berimbang.
Syamsuddin Arif lebih lanjut menjelaskan pentingnya melatih abstract thinking melalui filsafat. “Filsafat adalah knowledge for the sake of knowledge,” ujarnya. Hal ini menekankan bahwa filsafat melatih manusia untuk berpikir abstrak dan kritis, suatu kemampuan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi AI.
Ia memberikan contoh sederhana: belajar matematika bukan hanya untuk menghitung, tetapi untuk membangun analytical mind. Filsafat, menurutnya, berperan serupa dalam membentuk kemampuan manusia untuk memahami esensi dan makna di balik realitas.
Ia menggunakan analogi penjumlahan dalam matematika: 1 apel + 1 durian tidak menghasilkan 2 apel atau 2 durian. Namun, ketika diajarkan “satu saja”, itu mengacu pada konsep abstrak, kuantitas.
“Apa gunanya belajar satu? Belajar angka-angka itu? Untuk melatih abstract thinking,” tegas Arif.
Ketimpangan Pengetahuan di Masyarakat Muslim
Ketika ditanya mengenai keseimbangan antara pengetahuan praktis dan teoritis di masyarakat Muslim, Syamsuddin Arif mengakui adanya tarik-menarik. Ia menyoroti kebijakan pemerintah yang cenderung memprioritaskan sains dan teknologi untuk pembangunan fisik, seperti yang pernah diungkapkan Mahathir Mohammad yang fokus memberikan beasiswa untuk studi sains dan teknologi.
Namun, Arif mengingatkan bahwa masyarakat tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga jiwanya. “Membangun jiwa itu gimana? Ya, itu tadi, membangun jiwa, membangun mental capacity, intelektual skills,” paparnya.
“Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,” katanya mengutip lagu nasional. Tanpa keseimbangan antara aspek praktikal dan teoritis, pendidikan akan kehilangan wataknya yang humanis.
Ia prihatin bahwa aspek pembangunan jiwa ini seringkali terlupakan dalam kebijakan publik, seperti isu link and match antara perguruan tinggi dan industri yang cenderung mengkapitalisasi pendidikan ke arah industri.
Arif mengagumi proporsionalitas yang diterapkan di negara-negara seperti Jerman, di mana lembaga riset seperti DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) masih mengucurkan dana untuk penelitian manuskrip, termasuk dari Uni Eropa untuk penelitian manuskrip Muktazilah berbahasa Arab. Hal ini menunjukkan bahwa pemangku kebijakan di sana memahami pentingnya pengembangan humaniora.
Arif berharap akan ada individu-individu dengan kelapangan rezeki yang tergerak hatinya untuk membangun lembaga semacam itu secara berkesinambungan, seperti model wakaf di Turki atau Muhammadiyah di Indonesia.
Syifa juga menambahkan untuk menyuarakan perjuangannya di Muhammadiyah untuk mempertahankan jurusan-jurusan yang tidak hanya berorientasi vokasi, tetapi juga berorientasi pengetahuan, yang mengkaji secara serius teks-teks primer sebagai warisan Islam.
Filsafat Islam: Bukan Filsafat?
Di akhir diskusi, Syifa Amin Widigdo mengangkat keraguan sebagian kalangan yang menganggap filsafat Islam bukan bagian dari rumpun filsafat sesungguhnya.
Syamsuddin Arif menanggapi bahwa pandangan ini kemungkinan berasal dari mazhab filosofi analitik yang menganggap filsafat harus steril dari nilai-nilai budaya atau agama. Mereka cenderung hanya mengakui filsafat yang berakar dari Plato dan Aristoteles, yang menurut Arif merupakan bentuk eurosentrisme.
“Itu adalah bentuk eurosentrisme yang menolak keberadaan filsafat Hindu, Buddha, bahkan Islam sebagai filsafat sejati,” kata Arif. “Padahal,” tegasnya lagi, “menafikan filsafat Islam hanya karena tidak berakar dari Plato dan Aristoteles, adalah bentuk kejumudan.”
Di bagian akhir diskusi, keduanya sepakat bahwa dunia Islam membutuhkan lembaga yang mendorong konservasi dan pengembangan khazanah keilmuan klasik. Syamsuddin Arif mengungkapkan cita-citanya untuk mendirikan pusat studi pascasarjana yang benar-benar menekuni filsafat Islam secara serius.
Ia mengutip ungkapan Naquib al-Attas: “Ability without opportunity is useless, and opportunity without ability is valueless.” Maka, perlu sinergi antara kecakapan dan kesempatan, didukung oleh segelintir “a few good men” yang benar-benar komitmen menjaga warisan keilmuan Islam.
Melalui perbincangan ini, menjadi jelas bahwa filsafat sangat penting di era disrupsi AI. Justru di tengah kecenderungan teknokratis yang membebani manusia dengan kecakapan teknis semata, filsafat hadir sebagai penuntun refleksi.
Filsafat, dengan demikian, adalah upaya to humanize human being.