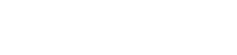MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Apakah seluruh kejadian di dunia ini dikendalikan oleh beberapa orang saja? Apakah Pandemi Covid-19 tidak nyata dan hanya pembentukan wacana semata? Apakah vaksinasi adalah program tersembunyi membinasakan umat manusia? Apakah bumi ini sebenarnya berbentuk datar?
Tak dipungkiri, pertanyaan dengan tema-tema seperti di atas nampaknya adalah ‘normal’. Beberapa kalangan bahkan bukan hanya bertanya, tapi meyakini secara apriori, haqul yaqin, bahwa memang demikianlah yang sebenarnya terjadi.
Di masa sulit apapun baik peperangan atau pandemi seperti sekarang, pemikiran konspirasi justru tumbuh subur. Para peneliti seperti Abalakina-Paap, Stephan, Craig, & Gregory (1999) hingga Grzesiak-Feldman (2013) jauh-jauh hari telah menyatakan bahwa orang akan mendukung pemikiran konspirasi ketika mereka diliputi kecemasan, kondisi serba tidak pasti dan rasa tidak berdaya.
Pada masa normal, pemikiran konspirasi tidak berdampak apapun selain wacana tandingan yang ganjil dan sebenarnya ‘sah-sah saja’. Narasi bumi datar oleh pendakwah Rahmat Baequni tidak mendapat spotlight dan efek yang besar selain perdebatan konsistensi hukum logika.
Tapi pada masa krisis, satu pemikiran konspirasi mampu membawa satu bentuk destruksi masal di tingkat sosial. Destruksi para penganut konspirasi ibarat orang yang rumahnya terbakar tapi lebih mendahulukan mencari alasan yang layak mengapa rumahnya terbakar daripada memadamkan api dan menyelamatkan orang-orang di dalamnya terlebih dahulu.
Belakangan, kita mengenal nama-nama pesohor media sosial yang membantah dampak berbahaya Covid-19 nyata. Dengan kata lain, mereka menganggap sedikitnya 4,3 juta jiwa manusia yang meninggal karena pandemi adalah hasil persekongkolan jahat seluruh tenaga medis dan rumah sakit di dunia untuk “mengcovidkan” status kesehatan seseorang.
Pernyataan mereka memperburuk penanganan Covid di Indonesia yang memang sudah tidak ideal sejak awal. Peneliti seperti Prooijen dan Douglas (2018) bahkan menyimpulkan bahwa teori konspirasi seringkali memiliki dampak nyata pada kesehatan, hubungan sosial, dan keselamatan orang lain.
Faham skeptisisme yang lebih cenderung ke paranoia seperti nalar konspirasi nyatanya bukan masalah negara berkembang saja. Negara maju seperti Belanda, Inggris, Amerika memiliki jumlah penganut konspirasi yang tidak sedikit. Pada konteks pandemi Covid-19, beberapa di antara mereka bahkan sempat menghancurkan menara 5G karena dianggap menyebarkan virus Corona.
Atas alasan itu, Jurnal medis internasional bergengsi The Lancet (2020) merilis hasil penelitian bahwa Covid-19 berasal dari patogen satwa liar. The Lancet di sisi lain berusaha mengikis prasangka liar bahwa Covid-19 adalah hasil rekayasa biologis laboratorium China untuk menyerang Amerika dan dunia.
Kenapa Teori Konspirasi Digandrungi?
Abad 21 diidentifikasi sebagai era Post-Modern yang ditandai dengan besarnya minat terhadap studi penunjang seperti Post-kolonial guna menilai kembali berbagai hal yang telah dianggap mapan. Cara pandang kritisisme dan skeptisisme pun digemari karena keberaniannya melawan kemapanan dan otoritas ilmu dengan cara meruntuhkannya, lalu menyusunnya ulang dengan menghindari bias subjektivitas dominasi kuasa.
Sepanjang berjalan dalam epistemologi yang ketat, gagasan post kolonial menjadi informasi alternatif yang penting diperhatikan. Tetapi ketika tidak, maka muncul berbagai kesimpulan unik, misalnya pernyataan Menteri India Biblab Kumar yang menyatakan bahwa teknologi internet sudah digunakan di zaman Mahabarata.
Di zaman ini pula, teknologi menciptakan realitas maya yang membuat seorang awam merasa sederajat dengan para pakar. Ukuran-ukuran ilmiah tak dianggap serius sebagai standar bersama untuk berdebat. Tak heran, tahun 2016 Oxford Dictionary menjadikan kata Post-Truth sebagai Word of the year.
Post-truth sederhananya adalah keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada sesuatu yang menarik emosi dan kepercayaan pribadi. Secara kasat mata, fenomena Post-Truth dapat dilihat dari besarnya kekuatan pendengung (buzzer) dalam membentuk opini lewat media sosial.
Situasi politik yang buruk di mana tidak ada penjelasan resmi yang bisa dipercaya, juga dianggap para peneliti menyuburkan dukungan terhadap nalar konspirasi, terutama oleh mereka yang secara partisan kalah, dirugikan atau merasa disisihkan.
Percaya Konspirasi Pertanda Tak Siap Terima Kenyataan
Van Prooijen & Jostmann (2013) menyatakan bahwa kepercayaan konspirasi lebih kuat ketika orang mengalami kesusahan sebagai akibat dari perasaan tidak pasti.
Michael A Peters (2020) bahkan menegaskan bahwa dukungan terhadap nalar konspirasi akan subur di mana situasi pemerintahan bersifat korup, otoriter dan tidak transparan. Tak lupa, kelompok dengan status, pendidikan dan ekonomi rendah juga dianggap lebih mudah terhasut oleh nalar konspirasi.
Fakta-fakta inilah yang kemudian tidak dipisahkan dalam memandang penyebab suburnya penganut teori konspirasi.
Mengapa Pemikiran Pengagung Konspirasi Layak Diabaikan
Setidaknya, ada tiga alasan utama mengapa kita perlu mendiamkan ajakan berdebat para pengagung teori konspirasi. Pertama adalah dari cara mereka berpikir, kedua adalah dari cara perolehan-pengolahan informasi (akses-proses data) dan ketiga adalah psikologi penganut Konspirasi.
Pertama, soal cara berpikir (nalar). Hampir seperti pemikiran mistik, nalar konspirasi termasuk dalam cara berpikir prediktif, yakni menerka sesuatu yang sedang dan akan terjadi di luar fakta empiris yang tersedia.
Meskipun nalar konspiratif menihilkan peran magis dan lebih pada menyambung benang-benang terpisah dari berbagai kejadian, nalar konspiratif telah memastikan hal yang belum diketahui dan belum tentu terjadi (bersifat potential, possibility) sebagai suatu hal yang sebenar-benarnya terjadi atau nyata-ada (fact or exist).
Dalam pengertian itu, nalar konspirasi lebih mirip kepada suatu keyakinan (iman) daripada ilmu. Karenanya diskusi se-ilmiah apapun tidak akan berfungsi sebab mereka mengunci pintu bagi kemungkinan kebenaran lain sedari awal. Sebagaimana konsep iman, hanya pengalaman eksistensial saja yang mampu membatalkan dan mengubah keyakinan mereka.
Kedua, soal cara perolehan-pengolahan informasi (akses-proses data). Penganut nalar konspirasi dikenal menyangkal semua informasi umum terkait data-data sains (data terbuka) yang lazim kita temui. Dengan meyakini data mereka sebagai kebenaran tunggal, mereka lupa bahwa kesimpulan sains bersifat dinamis, yakni kebenaran lama otomatis batal dengan ditemukannya kebenaran baru.
Di sinilah kerumitannya. Penganut nalar konspirasi selalu mengajak berdebat, namun meyakini bahwa data tandingan dari lawan mereka adalah data rekayasa. Jika data dari lawan secara masuk akal membantah teori konspirasi, mereka meyakini bahwa hal itu sudah direncanakan. Semua elemen lain seperti saksi ataupun bukti yang tidak menguntungkan juga diyakini adalah hasil sekongkol dan suap.
Uniknya, jika data yang dibawa oleh lawan mereka dianggap bersesuaian dengan teori konspirasi, maka mereka menerima dan menggunakannya untuk menguatkan teori mereka.
Di sisi lain, mereka meyakini bahwa semua ilmuwan di dunia terhimpun dalam satu kekuatan dogmatis bernama ‘elit global’ yang bersekongkol menghadirkan fakta palsu dengan tujuan jahat. Oleh karena itu, satu dua orang ilmuwan yang tidak representatif namun tampil keluar jalur dan vokal menyuarakan nalar konspirasi akan dianggap sebagai pahlawan.
Ketiga, soal psikologi penganut Konspirasi. Selain defensif dan denial, penganut konspirasi kerap disebut terjangkit perasaan narsisme kolektif. Peneliti seperti Cicchocka, Marchlewska, & Golec de Zavala (2016) menyimpulkan bahwa penganut konpirasi meyakini dirinya sebagai kelompok hebat namun orang lain tidak cukup menghargainya.
Cicchocka dkk lalu menjelaskan bahwa pandangan berlebihan tentang diri sendiri mereka itu membutuhkan validasi eksternal. Sebab, mereka meyakini bahwa kompetensi mereka dianggap sepele karena hasil sabotase oleh pemiliki kekuasaan.
Oleh karena itu, bagi kita pengabaian argumen mereka sebenarnya adalah tindakan yang cukup beralasan. Sebab kecilnya spotlight terhadap argumen mereka berbanding lurus dengan semangat mereka menyebarkan propaganda.
Teori Konspirasi dalam Perdebatan
Ya, tidak semua pemikiran konspirasi salah dan tidak bermanfaat. Dalam perjalanan sejarah seringkali isu-isu besar yang tak terselesaikan mengandung teori konspirasi. Wafatnya Soekarno, pembunuhan Anwar Sadat, G 30 S PKI, WTC 9/11, dan lain-lain lebih mungkin dipahami melalui teori konspirasi. Meski kenyataannya sulit melakukan verifikasi.
Meski demikian bukan berarti nalar konspirasi adalah layak digunakan di sembarang tempat. Menurut hemat penulis, nalar konspirasi penting untuk digunakan secara terbatas dalam isu politik pemerintahan lokal atau nasional.
Nalar skeptisisme dan kritisisme nampaknya dibutuhkan lebih-lebih oleh media massa untuk mengawasi kualitas sistem pemerintahan demokrasi setempat agar tidak disalahgunakan (abuse of power).
Selain berfungsi sebagai watchdog (pengawas kekuasaan), nalar konspirasi dalam konteks ini layak dilakukan mengingat petuah dari Lord Acton: “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
Contoh paling nyata adalah apa yang telah dilakukan oleh Washington Post (1972) dalam membongkar kasus Watergate yang akhirnya berdampak pada pengunduran diri Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan krisis konstitusional Amerika. Washington Post saat itu mengawali penyelidikan dengan teori konspirasi.
Tetapi tentu saja nalar konspirasi dalam konteks ini tidak digunakan sembarangan dalam membaca data. Media dan siapapun pemeran Watchdog tetap wajib menggunakan perangkat metode verifikasi yang ketat berdasarkan bukti dan bertahap seperti pekerjaan detektif dan jurnalisme investigasi.
Menurut Harris (2018), penggunaan nalar konspirasi dalam tugas ini berguna untuk menunjukkan tindakan lusuh individu dan kelompok politisi yang bersembunyi di balik informasi top down satu arah misalnya anggapan-anggapan bahwa ‘hanya pemerintah yang benar, selainnya hoax’.
Hal yang sama juga penting dilakukan pada dalil-dalil oposisi yang nampaknya alternatif namun sebenarnya menggali popularitas partisan.
Sebagai kesimpulan, barangkali harapan (sekaligus dilema) terbesar soal persebaran nalar konspirasi adalah sikap media. Keuntungan-keuntungan tertentu seringkali menjadi hambatan bagi mereka untuk tidak mendiamkan para pengagung konspirasi sekaligus tidak bersikap ideal sebagai watchdog terhadap pemerintahan. Pada akhirnya, keengganan mencari informasi alternatif pun menjadi pintu masuk bagi industri hoaks bekerja leluasa dan merusak penalaran yang sehat dan produktif.
Naskah: Affandi
Editor: Fauzan AS